Negara hukum diuji bukan saat perkara mudah dan hitam-putih, melainkan ketika publik terbelah antara rasa iba dan tuntutan keadilan
 |
| Oleh: Muhibullah Azfa Manik |
Tanamonews.com - Lampu ruang sidang selalu lebih dingin dari amarah seorang ayah. Di Pariaman, Sumatera Barat, seorang lelaki berinisial ED ditangkap karena membunuh F, pria yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya yang berusia 17 tahun. Laporan terhadap F telah masuk ke kepolisian pada 23 September 2025. Sehari kemudian, F ditemukan kritis di tepi jurang dan akhirnya meninggal. Peristiwa itu menjelma tragedi berlapis: dugaan kekerasan seksual terhadap anak, ledakan emosi orang tua, dan hilangnya satu nyawa di luar proses pengadilan.
Kasus ini segera merembet ke Senayan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan agar ED tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Ia menyerukan perlakuan adil dan meminta aparat mendalami kondisi psikologis sang ayah. Pernyataan itu mengundang simpati sekaligus kegelisahan. Di satu sisi, publik mudah memahami kemarahan seorang ayah yang anaknya diduga menjadi korban kekerasan seksual. Di sisi lain, negara hukum tak bisa berdiri di atas empati semata.
Empati dan Batas Hukum
Tak ada yang membenarkan kekerasan seksual. Kejahatan itu menghancurkan tubuh, jiwa, dan masa depan korban. Dalam banyak kasus, keluarga korban pun menanggung trauma yang panjang. Namun hukum pidana tidak dibangun untuk membalas luka dengan luka. Ia dirancang untuk memastikan setiap perampasan nyawa dinilai melalui prosedur yang adil dan terukur.
Dalam konstruksi hukum pidana, pembelaan terpaksa atau noodweer hanya dapat dibenarkan ketika ada serangan seketika dan langsung. Artinya, ancaman nyata sedang terjadi dan tak ada alternatif lain untuk menghindarinya. Dalam perkara ED, dugaan kekerasan seksual telah dilaporkan ke polisi. Serangan tidak sedang berlangsung ketika pembunuhan terjadi. Negara, setidaknya secara formal, telah hadir melalui proses hukum. Di titik inilah pembenaran emosional mulai berbenturan dengan syarat yuridis.
Namun hukum juga mengenal wilayah yang lebih subtil. KUHP baru memuat ketentuan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa hebat. Pasal ini membuka ruang bahwa seseorang yang bereaksi secara ekstrem akibat guncangan psikologis berat dapat dipertimbangkan untuk tidak dipidana. Inilah pasal yang dirujuk Komisi III. Tetapi ruang itu bukan karpet merah menuju pembebasan. Ia mensyaratkan pembuktian yang ketat, termasuk kemungkinan pemeriksaan psikiatri forensik, untuk memastikan bahwa ledakan emosi itu benar-benar lahir dari trauma akut yang tak terkendali.
Hukuman Mati dalam Bayang-Bayang KUHP Baru
Seruan DPR agar ED tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup memiliki pijakan yang tak sepenuhnya kosong. KUHP baru memosisikan pidana mati sebagai ultimum remedium, bahkan dengan masa percobaan sepuluh tahun. Hakim diwajibkan mempertimbangkan motif, tujuan, dan sikap batin pelaku sebelum menjatuhkan vonis. Dalam konteks ini, motif ED tidak terkait keuntungan ekonomi, kejahatan terorganisir, atau sadisme. Ia lahir dari kemarahan atas dugaan kekerasan terhadap anaknya.
Karena itu, penolakan terhadap hukuman mati bisa dipahami sebagai sikap yang sejalan dengan semangat pembatasan pidana paling ekstrem. Namun berbeda halnya bila pernyataan politik itu dimaknai sebagai pembenaran total atas tindakan menghilangkan nyawa. Di sinilah garis tipis itu berada: antara menolak hukuman yang tak proporsional dan menormalisasi vigilantisme.
Negara modern berdiri di atas monopoli penggunaan kekerasan yang sah. Ketika seseorang mengambil alih fungsi itu karena merasa negara lamban atau tak cukup memberi keadilan, kita sedang bergerak ke wilayah yang berbahaya. Hari ini mungkin publik bersimpati karena korban pembunuhan diduga pelaku kejahatan seksual. Besok, logika yang sama bisa dipakai terhadap orang yang baru dituduh, belum tentu terbukti.
DPR dan Ujian Pemisahan Kekuasaan
Pernyataan Komisi III juga menguji batas relasi antar-cabang kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia boleh mengkritik, memberi rekomendasi, bahkan mendorong perubahan kebijakan pidana. Namun ia tidak memiliki kewenangan membatalkan atau mengarahkan putusan hakim. Kekuasaan kehakiman, menurut UUD 1945, bersifat merdeka.
Selama pernyataan itu dipahami sebagai pandangan moral dan arah kebijakan, ia sah dalam ruang politik. Tetapi bila tekanan politik menjelma intervensi terhadap proses peradilan, preseden yang lahir bisa merapuhkan fondasi negara hukum. Hakim harus memutus berdasarkan alat bukti dan undang-undang, bukan berdasarkan resonansi opini publik atau tekanan elite.
Di titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib ED, melainkan integritas sistem. Jika setiap kasus emosional memancing campur tangan politik, ruang sidang berubah menjadi panggung negosiasi. Hukum akan dinilai bukan dari konsistensi, melainkan dari siapa yang paling mampu menggerakkan simpati.
Tragedi yang Lebih Dalam
Kasus ED menyimpan ironi yang tak bisa diabaikan. Ia berawal dari dugaan kekerasan seksual terhadap anak—kejahatan yang seharusnya mendapat respons cepat dan tegas dari negara. Bila proses penanganan berjalan lamban atau korban merasa tak terlindungi, kepercayaan publik terkikis. Dalam ruang ketidakpercayaan itulah amarah menemukan justifikasinya.
Karena itu, diskusi tak boleh berhenti pada soal layak atau tidaknya hukuman mati. Negara juga harus bercermin pada efektivitas perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Seberapa cepat laporan ditindaklanjuti? Seberapa serius pemulihan psikologis diberikan? Seberapa kuat jaminan bahwa pelaku tak akan mengulangi perbuatannya? Ketika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini lemah, masyarakat cenderung mencari keadilan dengan cara sendiri.
Namun mencari pembenaran atas pembunuhan bukan solusi. Nyawa tetap nyawa. Hukum harus berjalan. Empati terhadap ED tidak boleh berubah menjadi legitimasi kekerasan balasan. Pada saat yang sama, penghukuman yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan trauma dan motif juga berisiko menafikan dimensi kemanusiaan.
Di antara amarah seorang ayah dan kewibawaan negara hukum, kita dihadapkan pada pilihan sulit. Jalan tengahnya bukan dengan membiarkan emosi mengalahkan aturan, melainkan memastikan aturan cukup lentur untuk membaca tragedi secara utuh. Hakim perlu menggali kondisi psikologis, mempertimbangkan motif, dan menjatuhkan pidana yang proporsional. DPR boleh bersuara, tetapi ruang sidang tetap milik hakim.
Negara hukum diuji bukan saat perkara mudah dan hitam-putih, melainkan ketika publik terbelah antara rasa iba dan tuntutan keadilan. Dalam kasus ED, simpati mungkin melimpah. Tetapi keadilan tak boleh berubah menjadi gema kemarahan. Jika hukum tunduk pada emosi hari ini, ia bisa kehilangan wibawa besok.

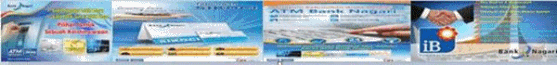
































0 Komentar